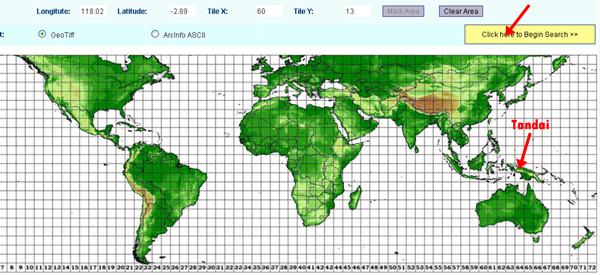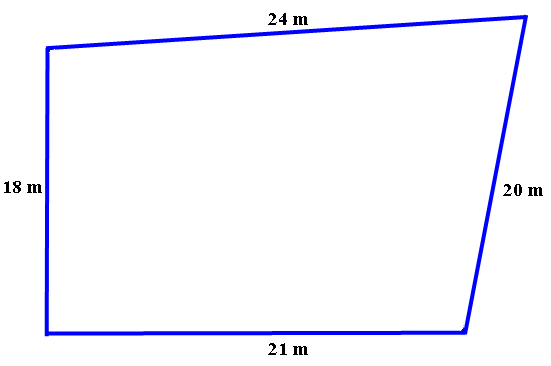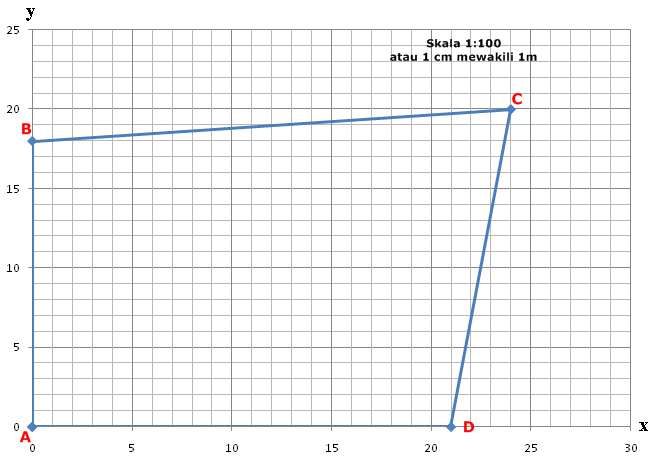Bentuk
permukaan bumi (relief) tidaklah statis melainkan dinamis, dalam
artian akan terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan yang
terjadi bisa karena faktor alam maupun karena faktor perbuatan manusia.
Perubahan karena faktor alam salah satunya yakni karena akibat aktifitas aliran
air yang merupakan aktor utama dalam proses erosi dan sedimentasi.
Hujan
yang jatuh ke permukaan bumi sebagian mengalir diatas permukaan tanah dan kemudian masuk ke sungai dan selanjutnya menuju outlet pembuangan di
waduk, danau dan laut. Aliran air yang mengalir di permukaan tanah ini yang sering disebut sebagai aliran permukaan
atau limpasan permukaan (run off).
Hujan
yang turun di pegunungan atau perbukitan akan mengalir menuruni lereng-lereng
dan dalam perjalanan air akan mengikis tanah-tanah yang gundul tanpa ditutupi
vegetasi. Proses pengikisan tanah oleh air ini yang disebut dengan erosi. Proses
erosi secara fisik dipengaruhi oleh iklim, sifat, tanah, topografi dan vegetasi
penutup tanah. Proses erosi sangat dominan terjadi pada tanah yang memiliki
kemiringan curam dan tanahnya labil serta tanpa ditutupi vegetasi. Pada
kemiringan yang curam kekuatan dan energi air akan meningkat secara signifikan
sehingga mampu untuk mengikis, mengangkut dan menghanyutkan tanah.
Proses
erosi yang berlangsung terus menerus akan merubah bentuk atau kontur permukaan
tanah, dimana lama kelamaan akan nampak parit-parit dengan kedalaman yang
bervariasi. Menurut bentuknya erosi dibedakan dalam erosi lembar, erosi alur, erosi parit, erosi tebing sungai dan tanah longsor.
Contoh bentuk-bentuk erosi yang terjadi di perbukitan Skyland Kota Jayapura ( Sumber: Laporan Kerja Praktek, 2011)
Tanah
hasil proses erosi akan diangkut oleh air dan diendapkan di badan-badan air dan sepanjang kanan-kiri sungai (bantaran, tanggul dan dataran banjir). Proses pengendapan sering disebut dengan sedimentasi dan
partikel-partikel tanah yang diendapkan disebut dengan sedimen. Sedimen yang
diendapkan di alur dan kanan kiri kiri sungai tidak akan diam terus disitu, melainkan akan terus bergerak dan
pergerakannya akan sangat cepat pada waktu banjir di sungai. Sedimen yang bergerak
didalam sungai wujudnya dapat berupa sedimen tersuspensi (suspended sediment) maupun
dalam wujud muatan dasar (bed load).
Proses
erosi tidak hanya terjadi di pegunungan atau perbukitan, namun juga terjadi di
sungai yakni, erosi pada dasar sungai, tanggul dan tebing sungai. Erosi di hulu sungai cenderung vertikal, sedangkan di hilir biasanya horizontal. Proses erosi
dan sedimentasi yang terjadi di sungai turut merubah bentuk lahan. Berikut ini
ada beberapa bentuk lahan yang merupakan hasil dari proses erosi dan
sedimentasi di sungai:
a.
Dataran
banjir (flood plain), merupakan dasar lembah di sisi sungai
yang terhilir yang mungkin terendam pada waktu air tinggi. Dataran banjir
terutama terbentuk dari hasil endapan sedimen di alur sungai dan pengendapan
sedimen halus pada daerah genangan pada waktu banjir.
Contoh sungai teranyam (sumber : google earth)
b.
Sungai
teranyam (braided stream),
bentuk sungainya seperti teranyam karena tanggul-tanggulnya dapat tererosi
dengan mudah dan cenderungg berpasir dengan lindungan tumbuhan yang sedikit. Bahan
dasar alur relatif kasar dan ukuran partikelnya heterogen. kemiringan sungai
teranyam lebih besar dari sungai berkelok-kelok.
Contoh sungai bermeander (sumber : google earth)
c.
Sungai
berkelok-kelok (meandering stream),
biasanya terletak di bagian hilir daerah aliran sungai yang landai dengan kecepatan aliran air yang lambat. Kelokan atau meandering terjadi
karena tanggulnya mudah tererosi. Kandungan sedimennya didominasi oleh lanau
dan lempung
d.
Percabangan
Sungai (Cut off), terjadi karena tanggul-tanggul sungai
mudah tererosi sehingga terjadi percabangan pada aliran. Cut off Umumnya terjadi
pada bagian sungai yang alirannya cenderung melambat.
e.
Oxbow
lake,
kalau dilihat oxbow lake awalnya
merupakan cut off namun telah
terputus. Erosi dan sedimentasi mengakibatkan terjadinya pergeseran alur sungai dan cut off menjadi benar-benar terputus dan menjadi semacam danau kecil atau
telaga yang tidak terkoneksi dengan alur sungai utama.
f.
Tanggul
alam (natural levees),
merupakan barrier di sisi kanan kiri sungai yang terbentuk dari sedimen yang mengendap.
g.
Delta,
terbentuk karena akumulasi sedimen yang terendapkan di muara sungai dan terkadang
sedikit menjorok ke arah pantai atau danau.
Kira-kira
demikian pembahasan secara singkat mengenai perubahan bentuk permukaan akibat aktifitas
aliran air. Semoga Bermanfaat. (*)
Sumber :
Lindsley Ray
dkk,1996., Hidrology untuk Insiyur, Penerbit Erlangga, Jakarta
Arsyad
Sitanala,1989.,Konservasi Tanah &
Air, IPB Press, Bogor